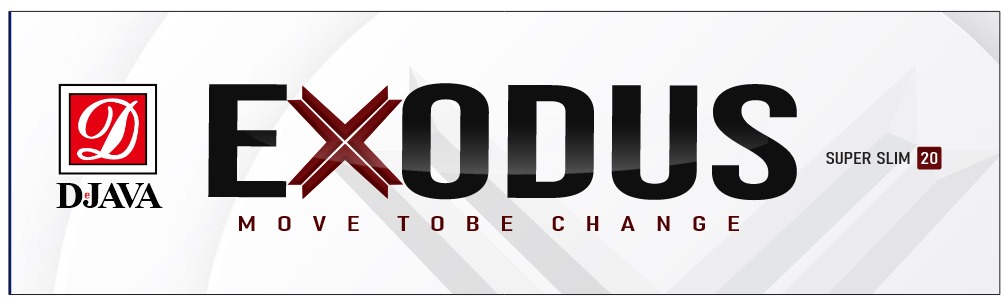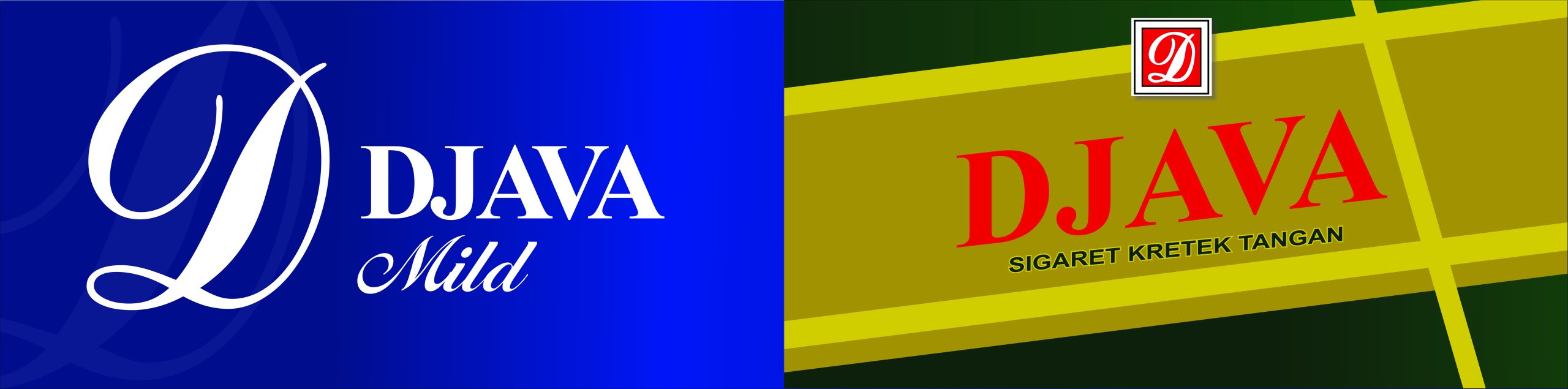Oleh: Hasibuddin
Opini – Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan kembali menjadi perbincangan hangat. Polemik ini menyeruak sejak kabar pergeseran jabatan eselon II bergulir di kalangan birokrasi dan publik. Namun, ternyata proses mutasi belum bisa dilaksanakan karena izin resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum turun.
Kepala BKPSDM Pamekasan, Saudi Rachman, sempat mengungkapkan hal itu pada sejumlah awak media, bahwa seluruh berkas yang diperlukan sudah diajukan secara daring, mulai dari hasil uji kompetensi, daftar riwayat hidup, hingga dokumen pendukung lainnya.
Secara prosedural, birokrasi di tingkat daerah memang harus menunggu restu dari dua lembaga tersebut. Inilah wajah formalitas birokrasi kita, penuh dengan norma, standar, prosedur, dan aturan yang kaku. Namun ironisnya, di sisi lain, jauh sebelum izin mutasi itu turun, gejolak di tubuh birokrasi Pamekasan sudah lebih dulu muncul. Kepala dinas di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) tampak berlomba menunjukkan kinerja instan, yang dalam praktiknya lebih menyerupai “akrobat” kebijakan ketimbang program yang benar-benar berbasis perencanaan jangka panjang.
Fenomena akrobat ini terlihat dari sejumlah proyek pembangunan, terutama infrastruktur jalan. Contoh paling kentara adalah pembangunan dan perbaikan jalan di kawasan tertentu. Jalan menuju pesantren yang diasuh Bupati diperbaiki dengan mulus. Begitu pula jalan lain yang menjadi akses ke rumah istri bupati, Nyai Tinuk Kholil, dipaving dengan rapi.
Memang benar, akses tersebut juga digunakan masyarakat luas. Namun, publik sulit menghapus kesan bahwa arah pembangunan lebih condong pada lingkaran keluarga kekuasaan. Kontras sekali jika dibandingkan dengan kondisi jalan desa di pelosok Pamekasan. Banyak warga desa yang harus mengandalkan swadaya, bergotong royong membeli semen seadanya untuk menutup lubang jalan agar kendaraan bisa lewat dengan aman. Di titik inilah publik menilai bahwa negara hadir tidak secara merata, melainkan hanya di sekitar pusat kekuasaan.
Masyarakat sebenarnya tidak anti pembangunan. Yang membuat mereka gerah adalah aroma ketidakadilan. Warga desa melihat bagaimana anggaran daerah bisa dengan cepat digelontorkan untuk akses yang bersinggungan langsung dengan elite, sementara jalan penghubung antardesa dibiarkan rusak bertahun-tahun. Perasaan ditinggalkan inilah yang pelan-pelan menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Isu Liar dan Absennya Klarifikasi
Di luar problem pembangunan fisik, isu lain justru berkembang liar di media sosial. Kabar beredar bahwa sejumlah kebijakan strategis bupati disebut-sebut kerap dipengaruhi oleh istri muda bupati Pamekasan. Entah benar atau tidak, kabar ini sudah kadung menjadi konsumsi publik. Sayangnya, pemerintah daerah jarang memberikan klarifikasi yang jernih.
Padahal, dalam era keterbukaan informasi, diam sama artinya membiarkan rumor menjadi “kebenaran baru” di mata masyarakat. Tidak heran bila asumsi publik berkembang liar, dari dugaan intervensi keluarga hingga praktik nepotisme dalam pembangunan. Pemerintah tampak gagap menghadapi isu-isu yang berseliweran, seakan lupa bahwa kepercayaan masyarakat adalah modal paling berharga dalam memimpin.
Apa yang terjadi di Pamekasan sejatinya bukan fenomena baru dalam dunia birokrasi. Max Weber, seorang sosiolog Jerman, pernah mengingatkan bahwa birokrasi ideal harus berdiri di atas rasionalitas, aturan, dan profesionalisme.¹ Birokrasi, dalam pandangan Weber, semestinya netral, tidak tunduk pada kepentingan personal apalagi keluarga penguasa.
Namun realitas di lapangan sering menunjukkan kebalikannya. Birokrasi mudah sekali berbelok mengikuti arah politik. Kepala dinas yang sejatinya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan teknis, justru tergiring pada kalkulasi politik menjelang mutasi. Mereka berusaha menampilkan “prestasi instan” agar dianggap loyal dan aman posisinya. Inilah wajah birokrasi yang kehilangan marwah, karena tak lagi bekerja untuk rakyat, melainkan demi menyelamatkan kursi jabatan.
Tan Malaka bahkan lebih tajam lagi. Dalam karya monumentalnya Madilog, ia menulis bahwa politik tanpa dasar filsafat dan moral adalah buta.² Jika politik dijalankan hanya untuk mengabdi pada kepentingan keluarga dan kelompok, maka arah pembangunan akan kehilangan orientasi. Bukan lagi untuk kemaslahatan rakyat, melainkan sekadar melanggengkan kuasa.
Mutasi: Antara Formalitas dan Barter Jabatan
Proses mutasi pejabat seharusnya berlandaskan pada prinsip meritokrasi—menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi, integritas, dan kinerja. Namun dalam praktiknya, publik kerap menduga bahwa mutasi hanya menjadi ajang barter jabatan. Siapa yang dekat dengan kekuasaan mendapat tempat aman, sementara yang dianggap kurang loyal bisa tersingkir.
Keterlambatan izin dari BKN dan Kemendagri justru membuka ruang spekulasi itu semakin luas. Selama jeda waktu ini, kepala dinas berlomba-lomba melakukan “akrobat” agar terlihat berprestasi. Sayangnya, akrobat semacam ini jarang berpihak pada kebutuhan rakyat banyak. Ia lebih sering diarahkan untuk menyenangkan atasan atau memperkuat citra politik keluarga penguasa.
Padahal, rakyat menunggu hal yang lebih substansial: kejelasan mutasi pejabat yang benar-benar sesuai aturan hukum, bebas dari praktik nepotisme, dan berorientasi pada pelayanan publik. Jika mutasi hanya menjadi perpanjangan kepentingan keluarga, maka publik akan semakin kehilangan harapan pada birokrasi.
Metafora “jalan” dalam konteks pembangunan Pamekasan sebenarnya sangat menarik. Jalan bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi juga simbol arah kebijakan. Ketika jalan menuju rumah elite mulus beraspal, sementara jalan rakyat di pelosok berlubang dan berdebu, di sanalah letak persoalan keadilan.
Akrobat kepala dinas boleh saja menimbulkan sorak sorai sesaat—misalnya, proyek cepat jadi, peresmian meriah, atau unggahan foto di media sosial. Tetapi jika jalannya hanya menuju rumah elite, bukan jalan rakyat, maka pembangunan itu kehilangan ruhnya. Rakyat akan melihat dengan jernih: negara hadir di sekitar kekuasaan, tetapi absen di rumah mereka.
Kepercayaan publik adalah mata uang politik yang paling berharga. Sekali kepercayaan itu hilang, sulit untuk mengembalikannya. Oleh karena itu, bupati dan jajaran Pemkab Pamekasan harus menyadari betul bahwa isu mutasi bukan sekadar persoalan administrasi kepegawaian, tetapi juga menyangkut legitimasi moral di mata rakyat.
Mutasi yang dilakukan sesuai aturan akan memberikan pesan bahwa birokrasi kita masih punya harapan. Namun jika mutasi hanya menjadi permainan kekuasaan, publik akan semakin skeptis. Ke depan, Pamekasan bukan hanya butuh pejabat yang pandai berakrobat, melainkan pejabat yang berani berpihak pada rakyat.
Penutup
Kini publik Pamekasan menunggu dua hal sekaligus. Pertama, kejelasan mutasi pejabat yang sesuai hukum dan prinsip meritokrasi. Kedua, arah pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan hanya melayani elite.
Mutasi jangan hanya menjadi ajang barter jabatan. Akrobat kepala dinas jangan berhenti pada proyek instan yang sarat kepentingan. Jika jalan yang dibangun hanya mengarah ke rumah elite, maka rakyat akan terus berjalan di atas jalan berlubang—jalan ketidakadilan dan jalan ketidakpercayaan.
Birokrasi semestinya berdiri di atas rasionalitas dan profesionalisme, seperti diingatkan Weber. Dan politik mestinya berlandaskan moral, seperti ditulis Tan Malaka. Bila keduanya diabaikan, maka Pamekasan hanya akan dipimpin oleh ilusi pembangunan, bukan oleh kenyataan yang menyejahterakan.
Catatan kaki:
1. Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology (University of California Press, 1978), hlm. 956.
2. Tan Malaka, Madilog (Jakarta: Lembaga Kebudayaan dan Penerbitan Balai Pustaka, 1951), hlm. xxx.