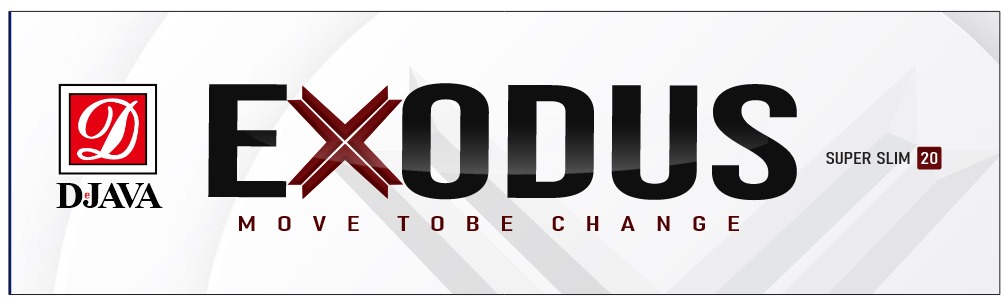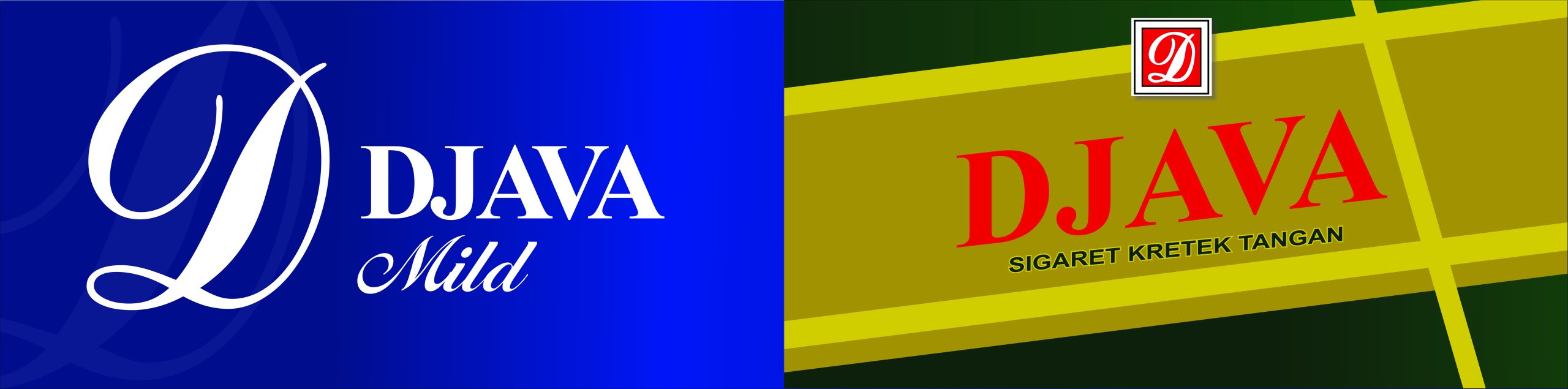Oleh: Survia Eva Putriani (Top 5 Dubas Kepri 2021)
Istilah “perempuan sebatas sumur, dapur, dan kasur” masih sering terdengar, bahkan di era modern ketika akses ilmu dan kesempatan terbuka luas bagi siapa saja. Pertanyaan yang muncul: apakah perempuan Indonesia sudah benar-benar memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan?
Jika pun peluang itu ada, apakah keberadaan perempuan dihargai secara substansial atau hanya sebagai formalitas pemenuhan kuota gender? Jangan-jangan, keterlibatan perempuan justru menjadi bagian dari sistem patriarki yang dibungkus modernitas—dilibatkan, tetapi hanya di ruang dan tujuan tertentu.
Faktanya, perempuan kerap dieksploitasi. Mereka dijadikan pemanis dalam proses lobi politik, dibebani tanggung jawab domestik sebagai kodrat, dan dipasang sebagai kandidat hanya karena aturan mewajibkan adanya keterwakilan. Namun ketika tiba pada proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan pembahasan isu-isu penting, suara perempuan sering diabaikan. Bahkan, tak jarang dianggap tidak layak bersuara.
Stereotip bahwa perempuan tidak mampu bernalar dan berlogika masih mengakar kuat. Padahal, urusan mempertahankan hidup—seperti mengurus dapur—adalah naluri manusia, bukan urusan gender. Kapasitas seseorang seharusnya diukur dari pengalaman, proses belajar, dan literasi, bukan dari jenis kelaminnya. Dalam perspektif humanisme, setiap individu memiliki potensi unik yang tak bisa dinilai hanya lewat label perempuan atau laki-laki.
Kehadiran perempuan dalam sosial-politik tidak boleh sekadar dijadikan pemanis. Sejarah menunjukkan banyak srikandi yang berperan besar dalam perjuangan bangsa. Cut Nyak Dien dan Cut Meutia bergerilya melawan penjajah, Kartini memperjuangkan pendidikan bagi perempuan, Marsinah melawan ketidakadilan hingga akhir tragis, dan Inggit Garnasih menopang perjuangan Soekarno dengan pengorbanan yang jarang disebut sejarah.
Semua itu membuktikan, perempuan memiliki kapasitas nyata dalam menentukan arah bangsa. Kehadiran mereka bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian penting dari dinamika sosial-politik.
Seperti ditegaskan Riane Eisler dalam The Chalice and The Blade, kerjasama antara laki-laki dan perempuan adalah kunci peradaban yang lebih baik. Dengan akses ilmu yang kini terbuka lebar, peningkatan kapasitas diri bukan lagi hal sulit. Artinya, setiap individu dengan akses yang sama seharusnya memiliki kesempatan yang sama.
Maka, sudah saatnya kehadiran perempuan dalam ruang sosial dan politik dipandang bukan sebagai pajangan atau formalitas, melainkan sebagai kekuatan substantif yang berperan penuh dalam menentukan arah bangsa.