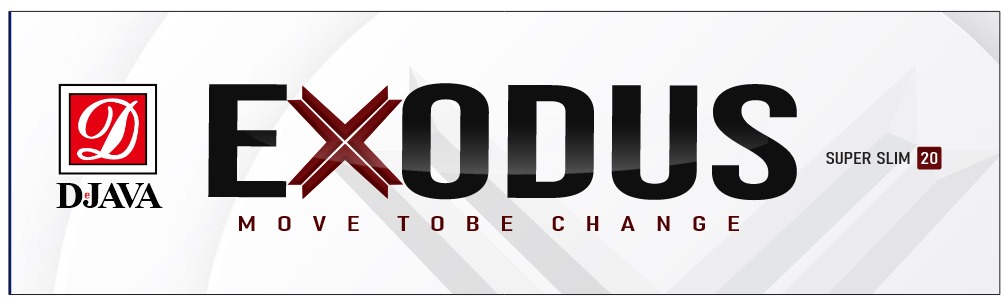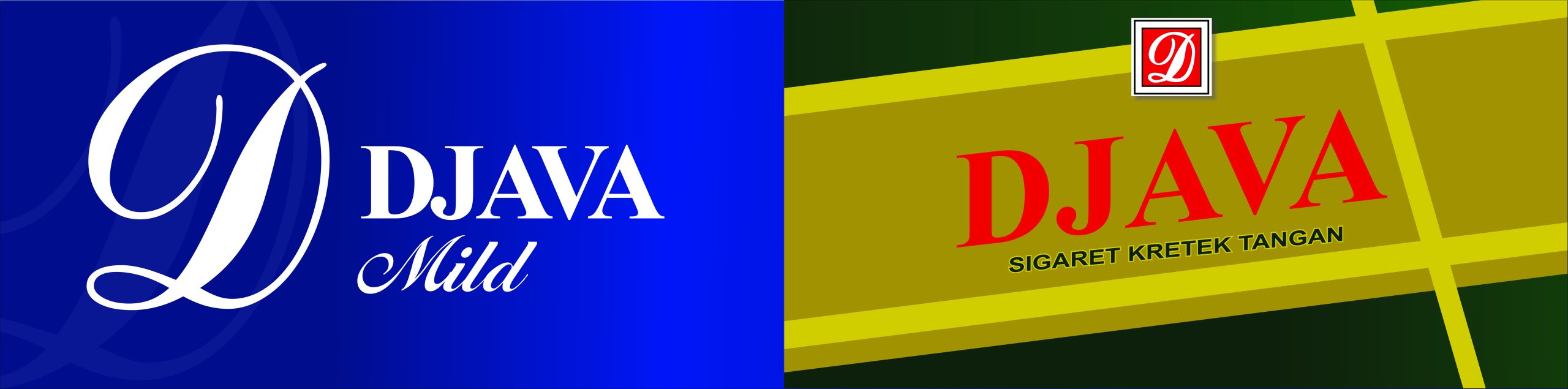Opini – “Kalau mau sejahterakan petani, rembuklah dengan saya. Jangan hanya mendengar bangsat-bangsat itu.” — Haji Her, pengusaha tembakau asal Pamekasan, Madura.
Kalimat lantang itu bergema dari Pamekasan, lalu menyebar ke ruang publik nasional. Haji Her, dengan bahasa sarkas namun jujur, menyampaikan kritik kepada Presiden. Ucapannya mungkin membuat sebagian orang terkejut, namun justru karenanya, pesan itu mungkin terasa menohok: petani merasa diabaikan.
Jika publik kaget gegara hanya menyimak video viral yang lewat di beranda media sosial, maka jurnalis -mungkin sebagian – yang ada di lapangan sempat mengernyitkan dahi. Demikian pula saya, yang saat itu ikut menyimak konferensi pers Haji Her, sebelum prosesi pelepasan konvoi 120 pick up rute Pamekasan-Suramadu.
Haji Her tak menyampaikan kritik secara tersirat, tapi terang-terangan. Semacam memberi alarm pada presiden agar jangan hanya mendengarkan bangsat-bangsat. Kalimat ini terlontar di akhir sesi konferensi pers.
Kata “bangsat-bangsat” jelas kasar, tetapi sesungguhnya mengandung pesan serius. Haji Her ingin Presiden tidak terjebak pada suara elite atau pihak yang mengaku mewakili petani, sementara realitas di ladang menceritakan kisah sebaliknya. Diksi “jangan hanya mendengarkan bangsat-bangsat” ini seolah menegaskan, petani kecil harus diajak bicara langsung, bukan hanya menjadi objek kebijakan yang dirumuskan di atas meja.
Diksi yang ia gunakan memang memicu pro dan kontra, namun justru karena kekasarannya, pesan itu menjadi sangat jelas: seolah ada kekecewaan mendalam terhadap cara negara memperlakukan petani tembakau.
Tulisan ini mencoba menelaah narasi kritik tersebut dari berbagai sisi: apakah ia sekadar ledakan emosi seorang pengusaha, ataukah ia adalah refleksi dari jeritan kolektif para petani yang selama ini terabaikan?
Bahasa Kasar, Pesan Serius
Dalam studi politik bahasa, pilihan kata sering kali mencerminkan kondisi batin dan konteks sosial penggunanya. Diksi “bangsat-bangsat” yang dipakai Haji Her mungkin terdengar kasar, bahkan tidak pantas dalam komunikasi formal. Namun jika ditelaah, ungkapan itu lebih dari sekadar umpatan; ia adalah simbol rasa kecewa yang mungkin lama terpendam.
Petani tembakau di Madura, misalnya, dalam beberapa tahun terakhir hidup dalam ketidakpastian harga setiap musim panen. Mereka berhadapan dengan pedagang perantara, perusahaan besar, hingga kebijakan pemerintah yang berubah-ubah terkait cukai dan tata niaga.
Situasi itu membuat mereka seolah menjadi korban berlapis: rugi di pasar, lemah di kebijakan, dan terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.
Bahasa kasar Haji Her menjadi alarm sosial. Ia berusaha menarik perhatian Presiden bahwa suara petani sejati tidak sama dengan suara elite yang sering mengaku mewakili mereka.
Sebagai seorang pengusaha yang sudah lama bergelut di dunia tembakau, – mayoritas publik sudah mengetahui – Haji Her tentu memiliki beberapa pengalaman. Baik yang manis, maupun yang ketir. Kalimat keras itu tentu tidak lahir dalam ruang kosong. Kritik Haji Her berakar dari realitas panjang tata niaga tembakau di Indonesia.
Pertama, ketergantungan pada industroi besar. Petani hanya menjual hasil panen, sementara harga dan kualitas ditentukan pembeli yang jauh lebih berkuasa. Pemerintah hadir, tetapi lebih sering dalam bentuk regulasi cukai atau kebijakan makro yang tidak secara langsung menyentuh kebutuhan petani kecil.
Kedua, minimnya ruang dialog langsung. Kebijakan strategis sering dibicarakan di Jakarta, bersama asosiasi besar atau kelompok yang dianggap representatif. Padahal, representasi itu kerap timpang. Suara petani kecil jarang sekali benar-benar sampai ke meja Presiden.
Ketiga, ketidakpastian regulasi. Beberapa kebijakan pemerintah tentang cukai hasil tembakau, pembatasan iklan rokok, hingga isu kesehatan publik, meski penting, kerap menambah beban psikologis bagi petani. Mereka merasa dihukum, padahal peran mereka hanyalah menanam dan menjual.
Dalam konteks ini, ucapan Haji Her menjadi representasi dari kritik lama yang selama ini tak kunjung terjawab.
Meski disampaikan dengan diksi yang mungkin kasar, sebenarnya ada harapan yang cukup jelas dari kritik Haji Her. Ia tidak sedang menolak pemerintah, apalagi mengajak konfrontasi. Sebaliknya, ia menginginkan negara hadir secara lebih jujur, langsung, dan terbuka.
Ia tidak menolak negara. Ia hanya menuntut agar negara hadir secara jujur. Harapan itu sederhana: kebijakan tentang tembakau jangan disusun semata-mata atas nama kesehatan publik, industri, atau kepentingan cukai, melainkan juga memperhitungkan realitas petani kecil yang menggantungkan hidupnya pada daun hijau itu.
Di titik ini, kembali terasa gema pikiran Tan Malaka. Ia menulis dalam Madilog:
“Kebenaran hanya bisa lahir dari keberanian, bukan dari kepatuhan membuta.”
Keberanian Haji Her menggunakan diksi kasar adalah bentuk keberanian rakyat melawan arus dominasi elite, Ia tidak ingin patuh membuta pada narasi besar negara yang sering mengorbankan petani di level bawah.
Harapan itu sederhana: Presiden harus mendengar suara petani langsung, bukan hanya laporan atau masukan dari kelompok tertentu. Dengan duduk bersama petani, Presiden dapat memahami realitas di lapangan, bukan sekadar angka-angka di laporan kementerian atau asosiasi.
Dalam politik partisipatif, kehadiran langsung pemimpin di tengah rakyat kecil adalah simbol kuat. Ia menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir di ruang elit, melainkan juga di sawah, ladang, dan pasar tempat rakyat berjuang.
Antara Didengar atau Diabaikan
Pertanyaan besar muncul: akankah kritik Haji Her didengar atau justru diabaikan?
Sejarah politik kita menunjukkan, kritik dari bawah sering kali berakhir dalam ruang sunyi. Negara lebih mudah mendengar suara elite dengan data, akses, dan pengaruh, ketimbang suara rakyat kecil yang hanya bermodalkan keberanian dan kejujuran. Namun, ada pula momen ketika kritik lantang memaksa perubahan.
Contoh paling sederhana adalah ketika harga komoditas anjlok dan petani melakukan protes terbuka. Tekanan publik akhirnya membuat pemerintah turun tangan. Namun, sering kali penanganannya bersifat reaktif, bukan sistemik.
Jika kritik Haji Her hanya dianggap luapan emosi, kemungkinan besar ia akan diabaikan. Tetapi jika ia dibaca sebagai representasi jeritan petani, mestinya pemerintah menjadikannya bahan refleksi serius.
Adalah hal yang wajar jika rakyat menyampaikan kritik. Haji Her misalnya, publik Madura khususnya Pamekasan, selama ini mengenal Haji Her sangat loyal pada petani. Beberapa media massa bahkan memuat narasi tentang jaminan dari Haji Her untuk memborong tembakau milik petani dengan harga yang impas, dalam artian menguntungkan para petani.
Sebagai salah satu pendukung Prabowo pada kontestasi politik pilpres 2024, Haji Her tentu berharap penuh agar Prabowo lebih peduli nasib petani.
Pesan Haji Her juga membuka diskusi lebih luas tentang relasi negara dengan petani. Selama ini, petani sering diposisikan sebagai objek: penerima subsidi, sasaran program, atau bagian dari data statistik. Jarang sekali mereka ditempatkan sebagai subjek yang ikut menentukan arah kebijakan.
Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Ironis ketika petani, yang mestinya berada di posisi terhormat, justru selalu di bawah tekanan.
Relasi negara dengan petani hanya bisa diperbaiki dengan cara sederhana: mendengar. Mendengar tidak sekadar hadir di acara seremonial, melainkan membuka ruang dialog rutin, menghadirkan perwakilan petani dalam forum kebijakan, dan memastikan suara mereka tercermin dalam keputusan negara.
Kritik, betapapun kerasnya, adalah bagian penting dari demokrasi. Dalam hal ini, kritik Haji Her bukan ancaman, melainkan peluang. Pemerintah bisa menjadikannya pintu untuk memperbaiki cara komunikasi dengan rakyat.
Jika pemerintah menanggapi kritik dengan defensif, menganggapnya sekadar ujaran kasar, maka peluang perbaikan hilang begitu saja. Tetapi bila kritik itu dibaca dengan rendah hati, pemerintah akan mendapatkan masukan berharga yang tidak bisa diperoleh dari ruang-ruang rapat formal.
Diksi “bangsat-bangsat” yang dilontarkan Haji Her memang mengusik. Namun di balik kekasarannya, tersimpan pesan serius: jangan abaikan suara petani. Kritik ini adalah refleksi dari kekecewaan panjang terhadap tata kelola kebijakan yang lebih sering memihak elite daripada rakyat kecil.
Kini bola ada di tangan Presiden dan pemerintah. Apakah kritik itu akan didengar dan ditindaklanjuti dengan dialog nyata, atau justru diabaikan hingga menjadi bara kekecewaan yang lebih besar?
Pada akhirnya, bahasa keras hanyalah pintu masuk. Yang lebih penting adalah substansi pesannya: petani ingin didengar, diakui, dan dilibatkan. Jika pemerintah mampu menangkap pesan itu, maka kritik Haji Her bukan sekadar amarah, melainkan momentum untuk memperbaiki relasi negara dengan rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan.
*Penulis adalah salah satu Member Patobin Cafe yang diberi amanah sebagai Pemimpin Redaksi Yakusa.id