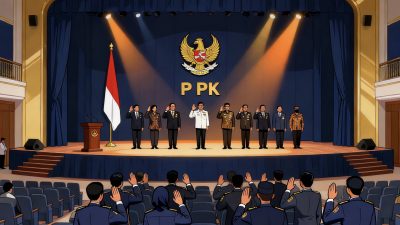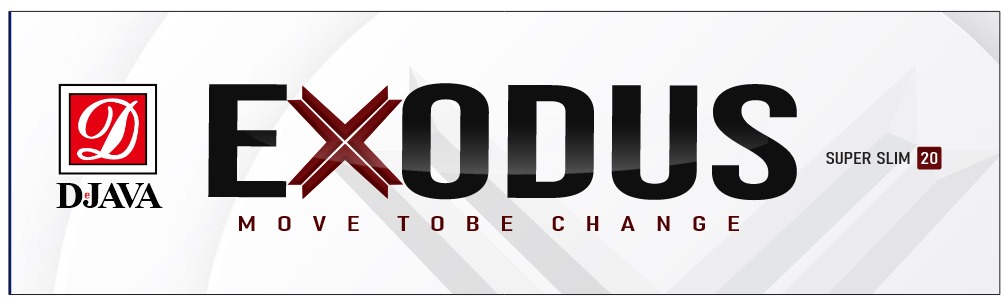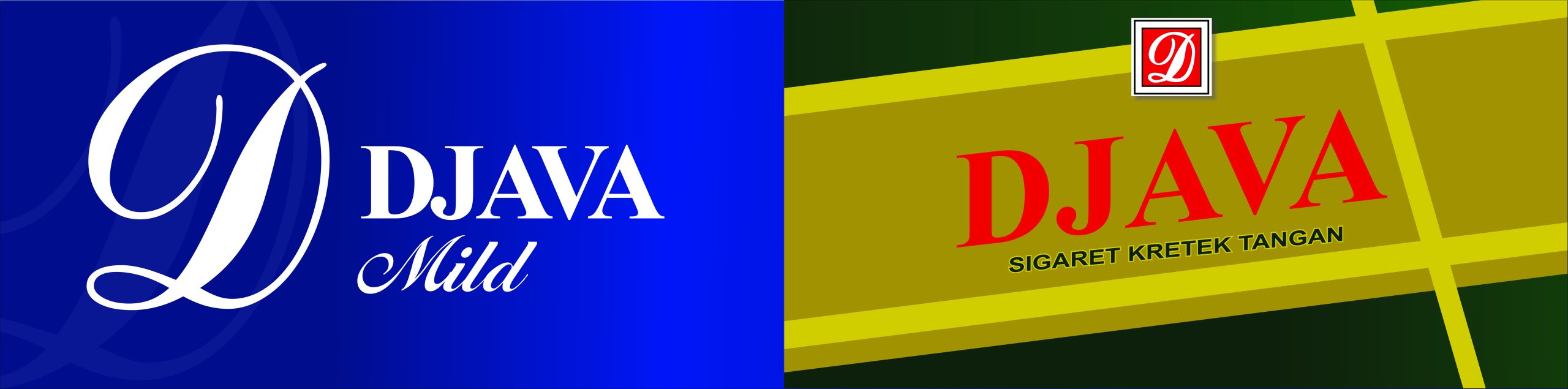Opini – Sejak kapan demokrasi di Sampang berhenti berdetak? Pertanyaan itu menggema di setiap sudut desa, dari Tapaan hingga Nepa, dari Marparan hingga Kadungdung. Sejak 2021, sebanyak 143 desa di Kabupaten Sampang terjebak dalam kevakuman politik.
Hak konstitusional warga untuk memilih pemimpinnya ditangguhkan tanpa batas waktu. Dalih berganti, alasan diperbarui, namun substansinya tetap sama, rakyat tidak lagi punya ruang untuk menentukan nasibnya sendiri.
Penundaan Pilkades serentak yang bermula pada masa pandemi kini bertransformasi menjadi krisis demokrasi yang akut. Apa yang dahulu disebut sebagai langkah antisipatif demi keselamatan publik kini menjelma menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah. Demokrasi akar rumput yang seharusnya menjadi fondasi kedaulatan rakyat justru menjadi korban dari birokrasi yang semakin menindas.
Krisis ini bermula dari terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021. Ketika banyak daerah sudah kembali menyelenggarakan Pilkades pascapandemi, Sampang justru menunda hingga 2025. Kini, menjelang akhir tahun tersebut, tahapan Pilkades belum juga dimulai. Alasan baru pun dilontarkan, menunggu peraturan pelaksana Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024.
Dalih ini terdengar administratif, tapi sesungguhnya menyingkap ironi besar. Regulasi nasional yang seharusnya memberi kepastian hukum justru dijadikan tameng untuk melanggengkan kekosongan kekuasaan.
Dampaknya kini nyata di lapangan. Ratusan desa dijalankan oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa yang ditunjuk langsung oleh Bupati. Para Pj ini, kebanyakan ASN dengan jabatan rangkap, sering kali absen dan minim interaksi dengan warga. Di banyak desa, pelayanan dasar lumpuh. Mulai dari pengurusan KTP tertunda, surat pindah tak selesai, dan pembangunan jalan berhenti di tengah proses. Rakyat menunggu, tetapi negara tak kunjung hadir. Lebih buruk lagi, tanpa pemimpin yang lahir dari rahim rakyat desa, mekanisme akuntabilitas hilang.
Namun di tengah stagnasi ini, ada ironi lain yang lebih menyakitkan. Pemerintah daerah justru tampak nyaman. Dua hari lalu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang dimintai keterangan, ia hanya menjawab singkat: “Kami menunggu PP dan Permendagri-nya.” Kalimat sederhana itu sesungguhnya potret nyata dari birokrasi yang kehilangan jiwa. Pemerintahan yang seharusnya proaktif menjaga hak politik rakyat kini justru menjadikan kelambanan regulasi sebagai alasan untuk berdiam diri.
Padahal, sistem hukum kita mengenal asas kontinuitas. Selama aturan baru belum diterbitkan, peraturan lama tetap berlaku. Artinya, PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 masih sah sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkades. Maka, yang hilang bukan dasar hukum, tetapi kemauan politik.
Kontras terlihat di Kabupaten Indramayu. Dalam kondisi hukum yang sama, pemerintah daerah di sana telah menetapkan tanggal Pilkades serentak pada 10 Desember 2025. Mereka bahkan mengukuhkannya melalui Peraturan Daerah yang disusun bersama DPRD—suatu bentuk komitmen pada supremasi hukum. Sampang, sebaliknya, memilih jalan pintas lewat SK Bupati, dokumen administratif lemah yang menyingkirkan fungsi legislatif dan menutup partisipasi publik.
Jakarta pun sebenarnya sudah menyalakan lampu hijau. Pada 22 Oktober 2025, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.5.5/5118/BPD, yang secara eksplisit memberi ruang bagi daerah melaksanakan Pilkades 2025–2026 dengan regulasi yang masih berlaku.
Artinya, tidak ada lagi alasan legal untuk menunda. Pemerintah pusat telah membuka jalan, dan kini semua tergantung pada kemauan Bupati Sampang.
Krisis di Sampang bukan krisis hukum, tetapi krisis hati dan kepemimpinan. Menunda Pilkades dengan alasan administratif hanyalah cara halus mempertahankan kendali politik. Pj desa yang tidak punya legitimasi rakyat jauh lebih mudah dikendalikan. Namun, strategi ini berbahaya: ia membunuh kepercayaan rakyat pelan-pelan. Demokrasi yang tak dihidupkan akan mati dalam diam.
Ketika rakyat kehilangan hak untuk memilih, mereka juga kehilangan kepercayaan bahwa suara mereka berarti. Balai-balai desa yang dulu hidup dengan musyawarah kini sunyi. Warga berhenti berharap karena tahu suara mereka tak lagi dihitung. Inilah titik paling gelap dari politik lokal.
Pemerintah daerah boleh berlindung di balik prosedur hukum, tapi moral politik tak bisa disembunyikan. Demokrasi bukan sekadar teknis pemilihan, melainkan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Jika hak itu ditangguhkan bertahun-tahun, maka yang mati bukan hanya proses politik, tapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Kini bola sepenuhnya berada di tangan Bupati Sampang. Jakarta telah memberi izin, rakyat sudah menunggu. Menunda lebih lama berarti memperpanjang harapan warga di 143 desa. Dan sejarah akan mencatat, apakah beliau memilih berpihak pada rakyat atau pada kenyamanan kekuasaan yang dikunci dari dalam.
Rakyat Sampang tidak menuntut banyak. Mereka hanya ingin memilih pemimpin mereka sendiri, sebuah hak sederhana yang dijamin konstitusi. Tapi jika hak sesederhana itu pun harus diperjuangkan berkali-kali, maka Sampang bukan hanya mengalami krisis hukum, melainkan krisis demokrasi paling telanjang di republik ini.
*Penulis adalah Pemimpin Redaksi Yakusa.id