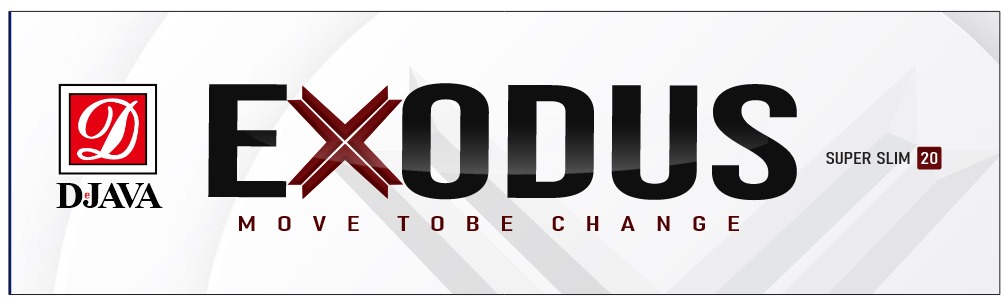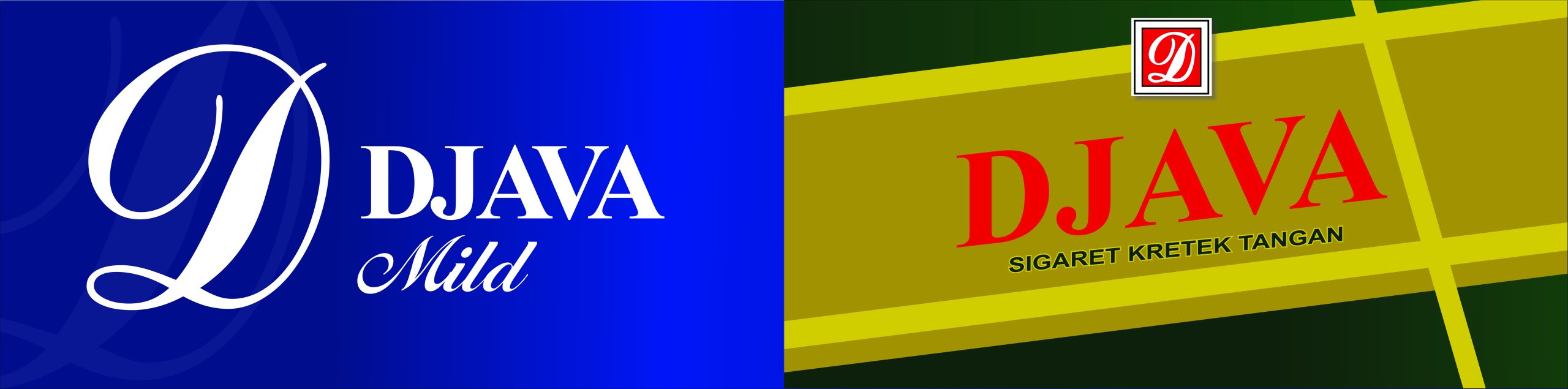Oleh: Hasibuddin*
OPINI – Tak elok rasanya bila kita terus menyoroti kelakuan para pejabat dengan segala macam akrobatnya, sementara media massa luput dari sorotan. Padahal, dua-duanya sama saja, sama-sama pandai berkelit di atas tali kepentingan.
Terus terang, sebagai pelaku media, saya pun kerap pusing—meski tidak sampai tujuh keliling—melihat akrobat narasi di ruang redaksi. Ada media yang semula garang, seolah ingin menabuh genderang perang melawan penguasa, tapi kemudian mendadak melunak, hanya karena dapur redaksi harus tetap “ngebul”.
Dua minggu lalu, Pamekasan diramaikan oleh pesan berantai tentang “tiga media yang bakal disuntik mati.” Saya tak tahu sumbernya, tapi istilah itu sendiri sudah cukup sensitif. Konotasinya kelam, seakan ada media yang hendak dimatikan (tak dapat anggaran) karena terlalu keras menyampaikan kritik. Soal benar tidaknya kabar itu, wallahu a‘lam.
Seseorang pernah mengirimi saya pesan singkat, “Media yang hidup dari anggaran publikasi pemerintah tak perlu terlalu keras.” Dalam arti lain, pesan itu berisi wejangan bahwa selama masih menyusu pada APBD atau APBN, sebaiknya media massa tahu diri. Tentu agak ironis bila mengaku anti pemerintah, menyerang membabi buta, tapi muaranya tetap menanti kucuran dana publikasi.
Lantas, mengapa harus menyerang dulu untuk kemudian merapat? Mengapa harus marah-marah jika akhirnya duduk manis di jamuan ramah tamah? Tapi begitulah dunia media hari ini—semua berujung pada kepentingan. Karena itu, saya selalu risih bila ada media yang mengaku paling independen, padahal di balik layar masih bergelut dengan kepentingan terselubung.
Relasi Media dan APBD Pamekasan
Meski tak semua, mayoritas media di Pamekasan pernah “kecipratan” APBD. Nilainya beragam, dan saya punya datanya. Sekadar gambaran sederhana, hampir semua media yang kini tampil sebagai oposisi, pernah pula mencicipi manisnya kue publikasi pemerintah. Kalau hari ini mereka menampilkan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, itu karena mungkin karena beragam faktor.
Maka ketika ada media yang tiba-tiba menyerang Pemkab Pamekasan habis-habisan, lalu melunak seketika, pantaslah kita bertanya: apakah ini bentuk akrobat?
Saya pernah diajak seseorang berdiskusi tentang pembagian anggaran publikasi. Saya bilang sederhana saja, asal pembagiannya tidak timpang, maka gejolak bisa dihindari. Tapi bila jatah media besar dan media kecil disamaratakan, maka kecemburuan pasti muncul. Tidak melanggar regulasi memang, tapi aroma ketidakadilan tetap terasa.
Di balik riuh isu “media hitam”, tersimpan kenyataan getir. Banyak media lokal kini bertarung bukan hanya melawan tekanan politik, tapi juga tekanan ekonomi. Media yang dulu lantang bersuara kini melemah. Bukan karena kehilangan idealisme, melainkan karena realitas, gaji karyawan harus dibayar, listrik redaksi harus menyala.
Mahbub Junaidi pernah menulis, “Pers adalah alat perjuangan, tapi juga alat perut.” Kalimat itu kini terasa nyata. Pers yang lapar bisa kehilangan arah, dan pejabat yang lapar kekuasaan bisa kehilangan akal sehat.
Titik Temu dan Krisis Kepercayaan
Namun jangan buru-buru menuding media saja. Di sisi lain, pejabat publik juga lihai berakrobat. Mereka bisa menunduk di depan atasan, tersenyum di depan kamera, lalu menegakkan kepala di depan rakyat—semuanya dalam satu tarikan napas.
Ada kepala dinas yang ahli membaca arah angin politik, berganti warna loyalitas secepat musim kampanye. Ada pejabat yang mahir membangun citra: tampil sederhana di publik, tapi di balik meja lihai merancang strategi agar kursinya aman.
Bagi sebagian pejabat, jabatan bukan lagi amanah, melainkan panggung. Maka akrobat menjadi alat utama untuk bertahan, melompat dari satu kepentingan ke kepentingan lain, dari satu kubu ke kubu berikutnya. Loyalitas bukan lagi kepada rakyat, tapi kepada kekuasaan yang paling kuat hari itu.
Tan Malaka dalam Madilog menulis bahwa bangsa yang berpikir kabur dan emosional tak akan pernah merdeka. Ia menyerukan pembebasan berpikir, namun di negeri ini, banyak yang justru sibuk memoles kepentingan. Media dan pejabat sama-sama terperangkap dalam kabut pragmatisme.
Akhirnya, media dan pejabat bertemu di satu titik. Saling membutuhkan dalam kepura-puraan. Pejabat butuh media untuk membangun citra, media butuh pejabat agar dapurnya tetap mengepul. Lahirlah simbiosis semu, saling menopang, tapi juga saling menjerat.
Dalam suasana seperti ini, kebenaran kehilangan panggungnya. Ia hadir sesaat, lalu tenggelam di bawah gemerlap pencitraan dan tekanan ekonomi.
Krisis kepercayaan terhadap media dan birokrasi adalah buah dari semua akrobat itu. Publik kini lebih percaya pada potongan video di media sosial ketimbang laporan berita resmi. Mereka lebih yakin pada bisik-bisik WhatsApp daripada rilis pers lembaga negara.
Namun masih ada yang bertahan: jurnalis yang menulis dengan hati, menolak amplop, dan memilih lapar daripada kehilangan nurani. Ada pula pejabat yang tetap tegak di tengah badai kepentingan. Mereka mungkin sedikit, tapi merekalah yang menjaga agar negeri ini tak sepenuhnya jatuh ke jurang absurditas.
Menutup Tirai
Mahbub Junaidi pernah berkelakar, “Kalau kebenaran bisa dibeli, maka yang miskin akan selalu salah.” Kalimat itu pahit tapi jujur.
Kita hidup di masa ketika kebenaran bergantung pada siapa yang membayar dan siapa yang menulis. Mungkin, sudah waktunya kita berhenti berakrobat.
Media harus kembali tegak sebagai penjaga nurani publik, bukan alat pencitraan kekuasaan. Pejabat harus kembali jujur pada rakyat, bukan pada kursinya. Sebab dalam demokrasi, kebenaran tidak butuh akrobat. Ia hanya butuh keberanian. Sesuatu yang dulu pernah diajarkan Tan Malaka, dan kini perlahan kita lupakan.
*Penulis adalah manusia yang punya kepentingan