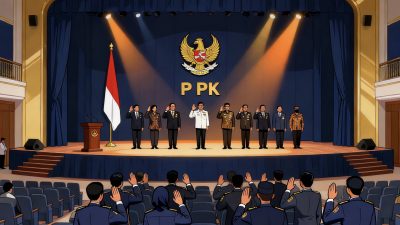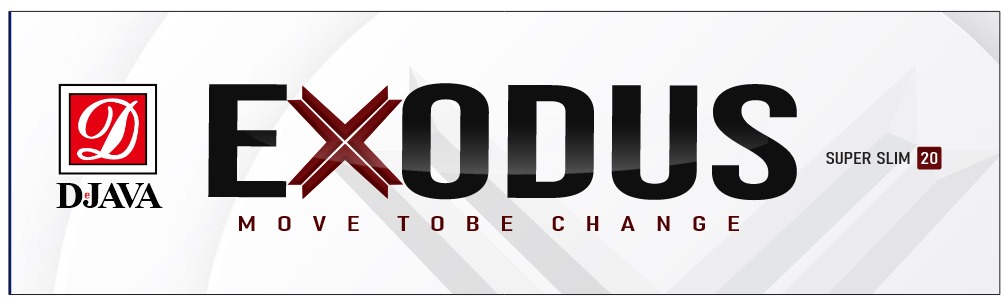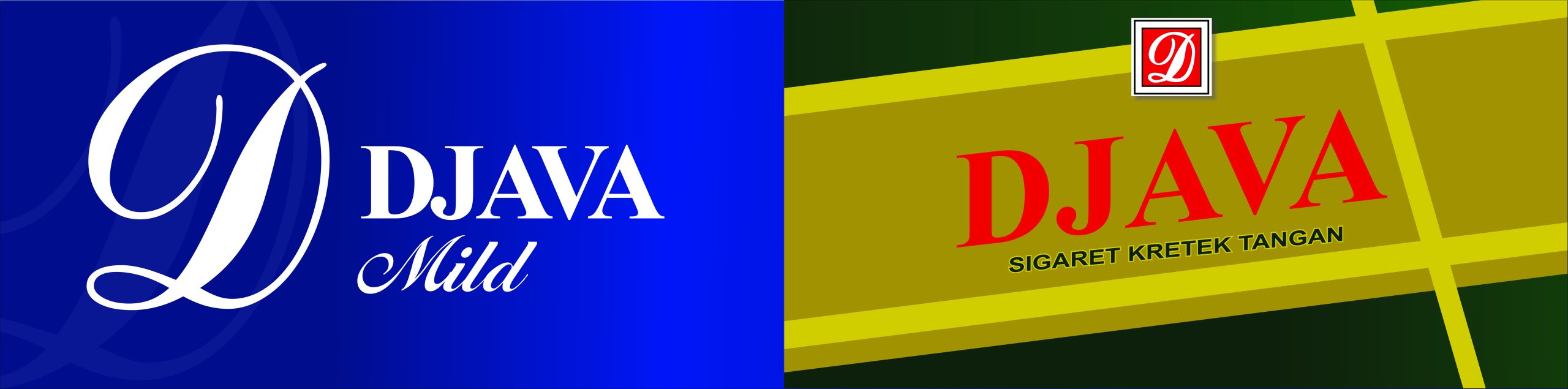Opini – Di Pamekasan, tren “ngopi merakyat” ala Bupati dan Wakil Bupati sedang hangat. Keterlibatan framing sejumlah media kerap menarasikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan gencar turun ke pelosok. Mulai dari menyapa petani, masuk gang sempit, duduk lesehan bersama warga.
Meski demikian, ada yang bilang kalau Pamekasan bisa jadi percontohan. Di sejumlah daerah ada Bupati dan Wakil Bupati yang justru terkesan saling sikut. Bahkan media ramai-ramai menulis ada Bupati dan Wakil Bupati yang sedang pecah kongsi, hingga berujung pada laporan pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pamekasan menyajikan hal yang berbeda. Bupati dan Wakil Bupati sedang adu tren ngopi merakyat. Pun demikian saat mendatangi korban bencana. Keduanya tak hadir bersamaan, tapi sama-sama datang memberikan dukungan dan bantuan. Ini tentu cukup menarik, sebab baik Bupati dan Wakil Bupati adalah satu-kesatuan yang tak terpisahkan dalam pemerintahan. Sederhananya, bila bupati berhalangan maka di sanalah peran Wakil Bupati untuk hadir ke lapangan.
Tren merakyat ala Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan ini tak perlu dihadapkan dengan model Head to Head atau pertandingan versus dalam istilah sepakbola. Tren ini memang seharusnya diapresiasi sebagai sebuah pola kesinambungan. Lalu, jika kemudian ada niat-niat lain dalam adu merakyat ini itu urusan belakang. Sebab pada akhirnya rakyat hanya menanti bagaimana kebijakan solutif dari pemerintah daerah lahir setelah label “merakyat” itu melekat.
Di permukaan, ini tampak sebagai kabar menggembirakan, bahwa pemerintah turun langsung dan mendengar keluh kesah, bukan sekadar berdiri dari podium resmi (baca: Pendapa)
Namun pertanyaan pentingnya: apakah ini lahir dari kesadaran kekuasaan untuk melayani atau justru hasil kebutuhan politik untuk membangun citra? Dalam beberapa tahun terakhir, gaya merakyat berubah dari sekadar pendekatan menjadi strategi dominan. Rakyat bukan lagi obyek, tetapi panggung. Di titik inilah kita perlu membaca fenomena ini dengan tajam namun adil, mengapresiasi kedekatan, sekaligus mencurigai potensinya menjadi kosmetik politik.
Sebagai sebuah gejala politik, pendekatan merakyat ini seolah menjadi standar baru dalam komunikasi kekuasaan lokal. Bupati dan Wakil Bupati tidak lagi menunggu rakyat datang ke pendopo, tetapi justru turun ke dusun, ikut memeriksa dapur, menyentuh realitas yang biasanya hanya dipaparkan lewat laporan birokrasi. Secara konseptual, ini merupakan koreksi terhadap jarak yang selama ini dianggap menjadi sumber kegagalan kebijakan.
Namun struktur kekuasaan tidak pernah netral. Kedekatan bisa lahir dari tanggung jawab, tetapi bisa pula diskenariokan sebagai investasi elektoral jangka panjang. Fenomena ini perlu dibaca bukan sekadar pada gestur yang tampak publik, melainkan pada konsistensi tindak lanjutnya. Soal apakah kunjungan ke lapangan diterjemahkan menjadi kebijakan solutif, atau berhenti sebagai dokumentasi visual untuk konsumsi media itu urusan nanti.
Fenomena ini sesungguhnya tidak muncul dalam ruang hampa. Ada transformasi preferensi publik yang semakin menuntut pemimpin untuk hadir secara fisik dan emosional. Era media sosial mempercepat perubahan itu. Kedekatan bukan lagi sekadar program, tetapi narasi visual yang mudah dikonsumsi dan dibagikan. Dalam konteks ini, gaya merakyat bukan hanya bagian dari kebijakan, tetapi juga komunikasi.
Maka pertanyaannya: apakah kedekatan ini berhasil mendekatkan pemerintah daerah dengan realita warga, atau justru sekadar menghadirkan ilusi belaka?
Karena jika sekadar hadir tanpa tindak lanjut kebijakan, maka yang diciptakan hanya momen emosional yang cepat menguap. Tetapi jika kunjungan itu menjadi instrumen percepatan respons —mengidentifikasi akar masalah langsung dari warga terdampak — maka pendekatan merakyat ini dapat menjadi model kepemimpinan efektif. Di sinilah signifikansinya. Bukan pada seberapa sering pemimpin turun lapangan, tetapi seberapa dalam struktur kebijakan yang berubah setelahnya.
Satu minggu ini, media membuat framing “Bupati Pamekasan Merakyat dan Sederhana”, gegara tertangkap kamera sedang meminum kopi di sebuah warung kecil. Lalu setelahnya, tren serupa muncul. Label Wakil Bupati Pamekasan merakyat karena tertangkap kamera sedang minum kopi di warung sederhana. Tempatnya memang terpisah, tapi framingnya sama yaitu Merakyat dan Sederhana.
Di Pamekasan, narasi merakyat Bupati dan Wakil Bupati juga tampak karena beberapa kali terlihat dalam momentum kemanusiaan dan pemberdayaan, semisal saat hadir langsung ke titik bencana, meninjau program pemberdayaan ekonomi kecil, atau mendampingi proses negosiasi sosial tertentu. Respons cepat semacam ini biasanya menciptakan legitimasi moral yang lebih kuat dibanding pernyataan tertulis atau konferensi pers formal. Namun publik juga semakin kritis. Mereka menilai bukan dari hadirnya figur, tetapi dari kelanjutan kebijakan setelah sorotan media mereda.
Ada risiko yang perlu diwaspadai, yaitu politisasi rasa. Ketika kedekatan dijadikan komoditas politik, publik bisa digiring untuk menilai pemimpin berdasarkan gestur emosional semata, bukan kinerja struktural. Ini berbahaya jika tidak diimbangi transparansi kebijakan dan keberanian membuka data. Karena relasi yang dibangun terlalu personal bisa menggeser rasionalitas publik ke arah fanatisme. Sebuah dinamika yang menguntungkan secara elektoral, tetapi rentan memudar saat kebutuhan riil masyarakat tidak berbuah solusi konkret.
Sebaliknya, jika gaya merakyat ini dikawal dengan mekanisme birokrasi yang adaptif, maka pendekatan ini bisa menjadi akselerator reformasi kebijakan publik. Keseriusan semacam ini akan membuat publik melihat kunjungan pemimpin bukan sebagai panggung pencitraan, melainkan sebagai langkah strategis pemerintah daerah turun ke akar persoalan.
Meski demikian, patut dicatat bahwa gaya merakyat yang kini dipraktikkan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan tidak semata berhenti pada simbol seremonial. Kehadiran mereka dalam berbagai ruang informal – bahkan di warung kopi warga – menjadi indikator bahwa pola interaksi kekuasaan telah mengalami desakralisasi. Jika dulu pendopo dianggap pusat koordinasi utama, hari ini meja kopi di pelosok desa bisa menjadi ruang diskusi kebijakan spontan. Pola ini, jika dikelola dengan kesadaran politik yang matang, dapat memperkuat legitimasi dan kepekaan terhadap aspirasi rakyat kecil.
Apresiasi wajar diberikan ketika pemimpin tidak sekadar hadir untuk agenda seremonial, tetapi benar-benar menyerap atmosfer sosial secara natural, tanpa jarak, dan tanpa protokol berlebihan. Warga menilai ketulusan bukan dari kata-kata, melainkan dari gesture yang tidak dibuat-buat.
Meski mungkin tidak satu meja di warung kopi, ketika Bupati atau Wabup duduk di warung kopi rakyat, mendengar langsung keluhan nelayan, petani, atau pedagang kecil, kehadiran pemerintah terasa konkret dan tidak abstrak. Di titik inilah pendekatan merakyat memiliki relevansi yang kuat.
Namun tren ini juga membuka arena perbandingan antar kepala daerah. Publik kini fasih membaca mana pemimpin yang merakyat dalam tanda kutip, dan mana yang benar-benar menjadikan kedekatan sebagai basis tata kelola. Banyak pemimpin di daerah lain hanya menjadikan warung kopi sebagai latar foto dokumentasi.
Di Pamekasan, praktik ini akan diuji bukan pada seberapa sering dilakukan, tetapi pada seberapa konkret hasil kebijakan yang lahir dari ruang obrolan sederhana itu.
Pada akhirnya, pendekatan merakyat bukan tujuan, melainkan metode. Ia akan bernilai jika dimaknai sebagai instrumen memperpendek jarak negara dengan realitas rakyat. Tetapi ia juga bisa menjadi jebakan jika berhenti sebagai estetika politik.
Tulisan ini tidak hendak menghakimi, melainkan mengajak publik dan pemangku kebijakan untuk membaca fenomena ini secara lebih mendalam. Tujuannya satu, agar kedekatan tidak berubah menjadi ilusi.
Jika kedalaman kebijakan menjadi arah akhir dari kedekatan ini, maka Pamekasan sesungguhnya sedang berada di jalur yang tepat. Tetapi jika kedekatan hanya menjadi pola komunikasi elektoral semata, maka kita akan kembali pada siklus lama. Penuh tepuk tangan tapi minim transformasi. Di sinilah ujian terbesar kepemimpinan modern diuji. Inilah momen di mana merakyat harus dimaknai bukan sekadar gaya, melainkan tanggung jawab struktural.
Penutup dari fenomena semacam ini sesungguhnya bukan terletak pada riuh sorak publik hari ini, tetapi pada ingatan sejarah yang akan menilai konsistensi pemimpin ketika sorotan kamera telah pergi. Kepemimpinan yang merakyat sejati tidak lahir dari dramaturgi, melainkan dari kedewasaan melihat rakyat bukan sebagai objek politik, melainkan sebagai subjek martabat.
Di era ketika jarak antara penguasa dan rakyat semakin tipis secara visual namun bisa tetap jauh secara struktural, para pemimpin diuji bukan pada seberapa sering hadir di tengah rakyat, melainkan seberapa sungguh memindahkan suara mereka ke dalam kebijakan yang efektif. Jika kedekatan ini menjadi jembatan menuju kebijakan yang lebih adil dan manusiawi, maka sejarah akan mencatat Pamekasan sebagai ruang pergeseran paradigma kepemimpinan baru.
Tetapi jika kedekatan hanya berhenti sebagai narasi visual tanpa perubahan mendasar, rakyat akan tetap menjadi penonton dari drama yang tak pernah selesai. Pada akhirnya, kemuliaan sebuah kepemimpinan tidak ditentukan oleh seberapa akrab ia difoto bersama rakyat, tetapi seberapa dalam rakyat merasakan keberpihakan dalam hidup mereka sehari-hari.
Di titik reflektif inilah kita menyadari: merakyat bukan soal turun ke bawah, melainkan bersedia merendahkan ego kekuasaan di hadapan realitas yang sering tak terdengar. Sebab yang paling menentukan bukan momen ketika pemimpin hadir di tengah rakyat, tetapi ketika rakyat merasa pemimpin benar-benar hadir dalam hidup mereka.