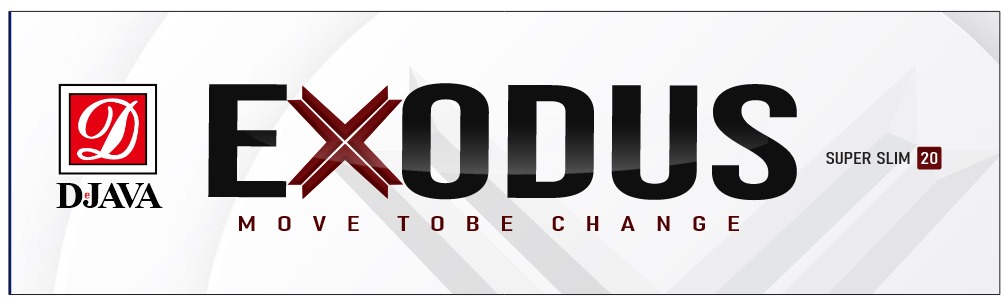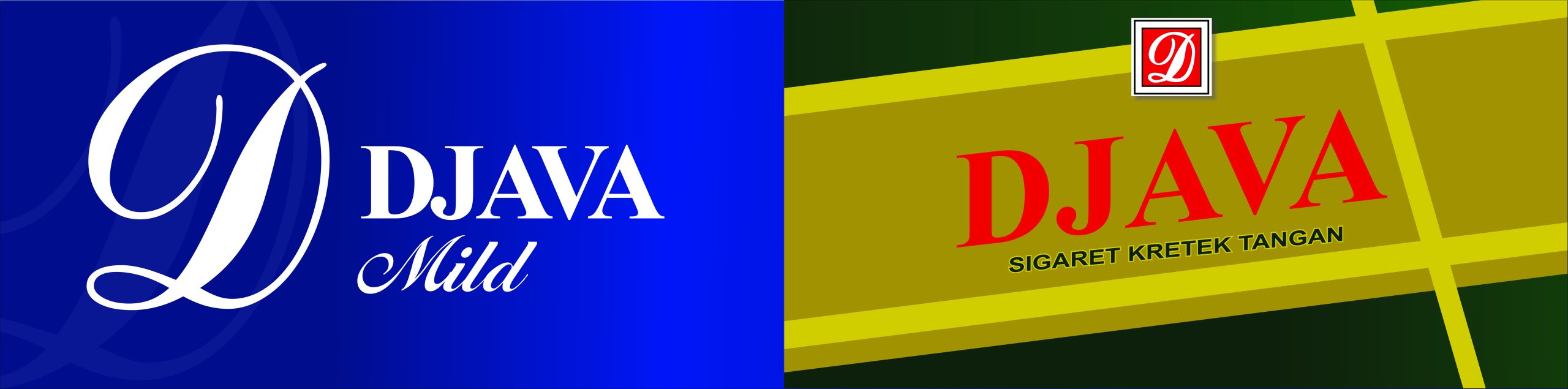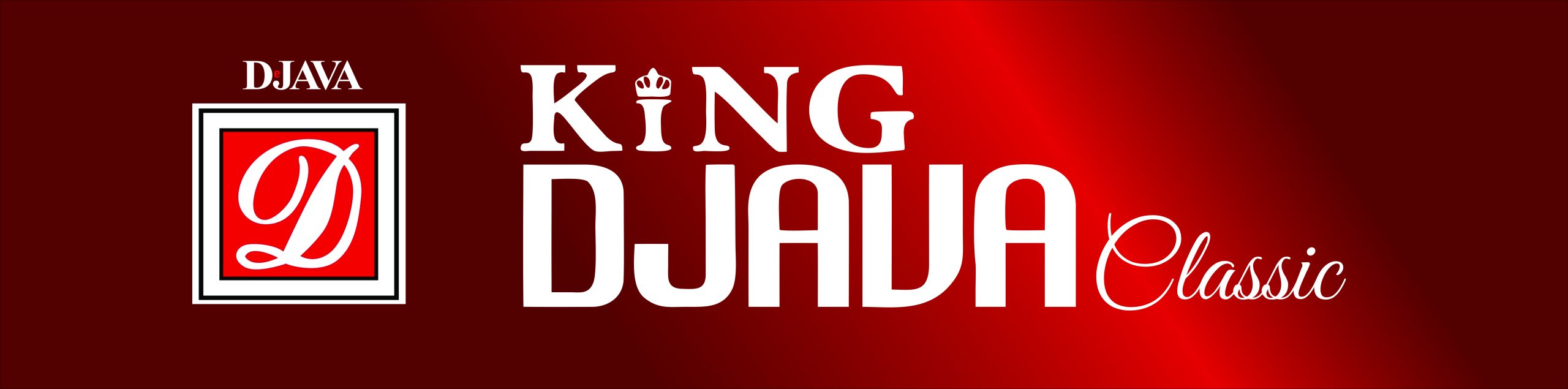Oleh: Hasibuddin
Opini – Demonstrasi mahasiswa yang mengguncang berbagai kota di Indonesia dalam beberapa hari terakhir telah membuka kembali ruang refleksi kita tentang cinta tanah air.
Dari Jakarta, Makassar, Surabaya hingga Bandung, ribuan mahasiswa turun ke jalan menolak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, mulai dari isu tunjangan anggota DPR yang fantastis hingga kematian seorang pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan taktis polisi.
Sementara itu, aparat kepolisian berdiri di barisan terdepan untuk menghadang, menjaga ketertiban, bahkan dengan risiko bentrok fisik.
Fenomena ini membuat saya teringat pada Kumbakarna dan Wibisana, dua adik rahwana, dalam epos Ramayana yang kisahnya tak lekang oleh zaman. Meski berasal dari dunia pewayangan, keduanya seakan menjelma kembali dalam dinamika bangsa hari ini.
Kumbakarna melambangkan nasionalisme absolut, atau kesetiaan total pada negara tanpa syarat. Sementara Wibisana mewakili moralitas, yakni keberanian berpihak pada kebenaran meski harus dianggap pengkhianat.
Kumbakarna atau Wibisana
Kita perlu mengenal siapa Kumbakarna. Dia adalah raksasa perkasa, adik Rahwana, atau anak kedua dari pasangan Resi Wisrava dan Dewi Kekasi. Kumbarkarna tidak pernah menyetujui penculikan Dewi Sinta. Sikapnya itu membuatnya berseberangan dengan kakaknya, Rahwana. Meski demikian Kumbakarna tak pernah menyampaikan protes yang amat keras. Kumbakarna memiliki kebiasaan tidur yang panjang bahkan hingga berbulan-bulan. Kata Kumbakarna, tidur itu bisa membuatnya terhindar dari perbuatan tercela, sebagaimana wataknya yang seorang pertapa.
Ia tahu perbuatan kakaknya salah dan akan membawa bencana bagi Alengka. Namun ketika perang pecah, ia memilih bangkit dari tidurnya dan mengangkat senjata membela tanah air.
Bagi Kumbakarna, kesetiaan pada negeri tidak bisa ditawar. Ia lebih memilih mati di medan perang daripada melihat Alengka runtuh, meskipun ia sadar pihak yang dibelanya berada di jalur keliru. Dia maju ke medan perang bukan untuk membela kakaknya yang lalim, tapi demi negara yang diobrak-abrik pasukan Sri Rama. Sikapnya inilah yang menjadikannya simbol patriotisme mutlak, Right or Wrong Is My Country (benar atau salah adalah negaraku.
Berbeda dengan Kumbakarna dengan sikap nasionalismenya, Wibisana memilih jalan berbeda. Sejak awal ia lantang menasihati kakaknya untuk mengembalikan Sinta kepada Rama. Baginya, mempertahankan kesalahan hanya akan menghancurkan Alengka. Tetapi Rahwana menolak dan mengusirnya.
Dalam titik itu, Wibisana memilih meninggalkan keluarganya dan berpihak kepada Rama. Keputusan itu membuatnya dicap sebagai pengkhianat, namun justru di situlah integritasnya teruji. Ia menegakkan dharma, sebuah kebenaran universal di atas ikatan darah dan tanah air. Bagi wibisana kebenaran atau moralitas melewati batas teritorial wilayah bahkan ikatan darah. Wibisana menempuh jalan dengan menyeberang ke pihak Sri Rama.
Dalam konteks hari ini, sikap itu kita jumpai pada aparat kepolisian. Mereka berdiri sebagai benteng negara. Meskipun mungkin secara pribadi sebagian polisi memahami keresahan mahasiswa, sumpah dan tugas membuat mereka tetap harus menjalankan perintah.
Mereka menjaga gedung DPR, melindungi pejabat, membubarkan kerumunan, menembakkan gas air mata, bahkan menghalau massa yang mereka tahu adalah sesama anak bangsa. Seperti Kumbakarna, polisi menjadi wajah kesetiaan mutlak pada negara, bahkan ketika negara sedang dipertanyakan legitimasi moralnya.
Sementara itu, mahasiswa digambarkan sebagai sosok Wibisana modern. Mereka mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil, menolak privilese anggota DPR di tengah penderitaan rakyat, dan menuntut keadilan atas kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas rantis polisi. Mereka tahu risiko turun ke jalan dengan dianggap sebagai perusuh, lalu ada ancaman penangkapan, bahkan kekerasan aparat. Namun mereka tetap memilih berpihak pada suara hati dan kebenaran, demikian lah sikap Wibisana. Baginya kebenaran diatas segalanya.
Relevansi Politik dan Demokrasi Indonesia
Ketika mahasiswa berhadap-hadapan dengan polisi di jalan, sebenarnya yang bertemu adalah dua wajah cinta tanah air. Polisi mewakili nasionalisme ala Kumbakarna, sedang mahasiswa mewakili moralitas ala Wibisana.
Dilema ini bukan persoalan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan persoalan cara mencintai negeri. Polisi takut kritik berlebihan akan mengancam stabilitas. Mahasiswa takut kesetiaan buta akan melanggengkan ketidakadilan. Keduanya sama-sama berangkat dari cinta, hanya berbeda dalam tafsir dan jalan.
Masalah muncul ketika salah satu sikap berdiri terlalu dominan. Jika semua orang menjadi Kumbakarna, negara akan tampak kokoh, tetapi tanpa koreksi bisa terjerumus dalam tirani. Jika semua orang menjadi Wibisana, negara penuh idealisme, tetapi bisa hancur oleh konflik dan perpecahan tafsir.
Indonesia hari ini berada dalam ketegangan yang sama seperti Alengka di masa Rahwana. Pemerintah, melalui DPR, membuat kebijakan yang ditolak rakyat. Aparat mengamankan, sementara mahasiswa melawan. Media sosial penuh dengan stigma “pengkhianat” untuk mereka yang mengkritik, dan sebutan “alat kekuasaan” untuk mereka yang setia membela.
Dalam kondisi ini, pelajaran dari Epos Ramayana menjadi relevan. Kita tidak bisa hanya bergantung pada nasionalisme Kumbakarna, karena itu akan menutup ruang kritik. Namun kita juga tidak bisa hanya meniru moralitas Wibisana, karena tanpa kesetiaan, bangsa bisa tercerai-berai.
Demokrasi membutuhkan keduanya, yakni kesetiaan yang menjamin stabilitas, dan moralitas yang menjaga agar stabilitas itu tidak dibangun di atas ketidakadilan. Polisi harus tetap patriotis, tetapi juga terbuka pada suara rakyat. Mahasiswa harus tetap kritis, tetapi tetap mengedepankan cara-cara damai.
Menuju Jalan Tengah
Apa yang bisa dilakukan? Pertama, negara harus memahami bahwa kritik mahasiswa bukanlah ancaman, melainkan alarm moral. Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi, bukan pengkhianatan. Polisi yang represif justru bisa menjadikan mereka Kumbakarna yang mati sia-sia, setia pada negara yang menolak belajar dari kesalahan.
Kedua, mahasiswa juga harus menjaga agar protesnya tidak jatuh ke dalam kekerasan yang destruktif. Wibisana menang bukan karena teriakannya paling keras, tetapi karena konsistensi moralnya. Ia berpihak pada kebenaran, bukan pada kepentingan sesaat.
Ketiga, publik harus berhenti melihat perbedaan ini dalam dikotomi hitam-putih. Baik Kumbakarna maupun Wibisana sama-sama mencintai tanah air, hanya dengan cara berbeda. Yang dibutuhkan adalah dialog, bukan bentrokan, sinergi, bukan saling curiga.
Kisah Kumbakarna dan Wibisana mengajarkan bahwa cinta tanah air bisa lahir dalam dua wajah: kesetiaan tanpa syarat dan keberanian berpihak pada kebenaran. Dalam demonstrasi mahasiswa vs polisi hari ini, kita melihat kedua wajah itu berhadap-hadapan.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: Apakah kita hanya akan memilih nasionalisme Kumbakarna yang setia meski salah, atau moralitas Wibisana yang benar meski dituduh berkhianat?
Jawaban terbaik mungkin bukan memilih salah satunya, tetapi meramu keduanya. Menjadi bangsa yang setia pada tanah air seperti Kumbakarna, namun juga berani berpihak pada kebenaran seperti Wibisana. Hanya dengan keseimbangan itulah, Indonesia bisa berdiri tegak bukan hanya karena loyalitas, tetapi juga karena kebenaran yang dijunjung tinggi.
*Penulis adalah warga Indonesia yang menyukai pewayangan