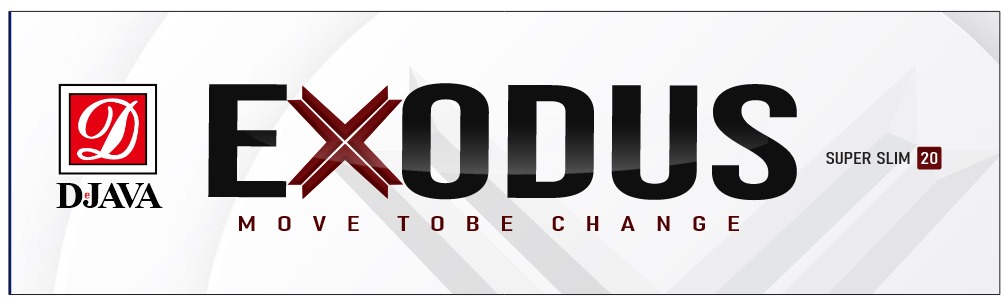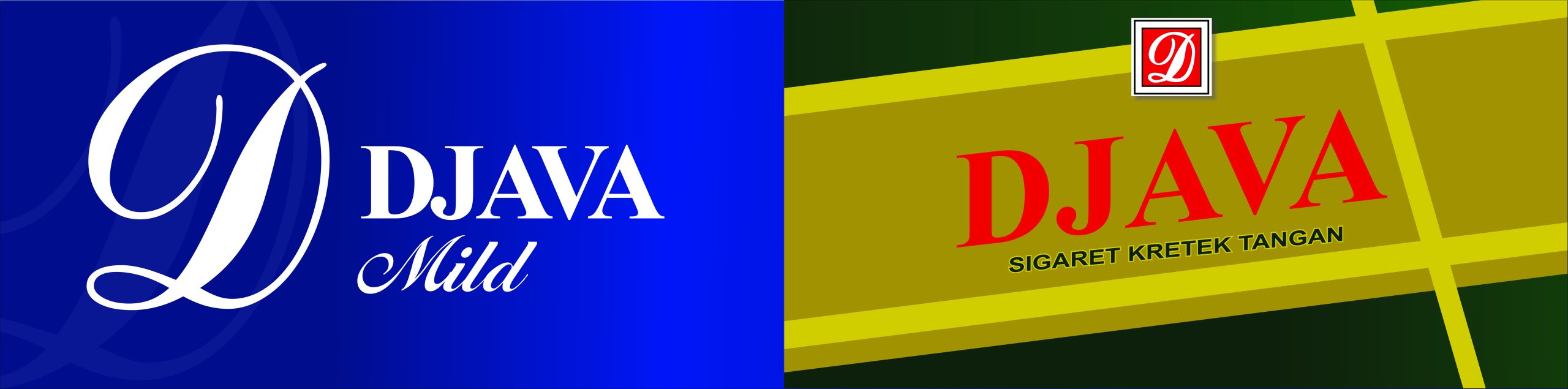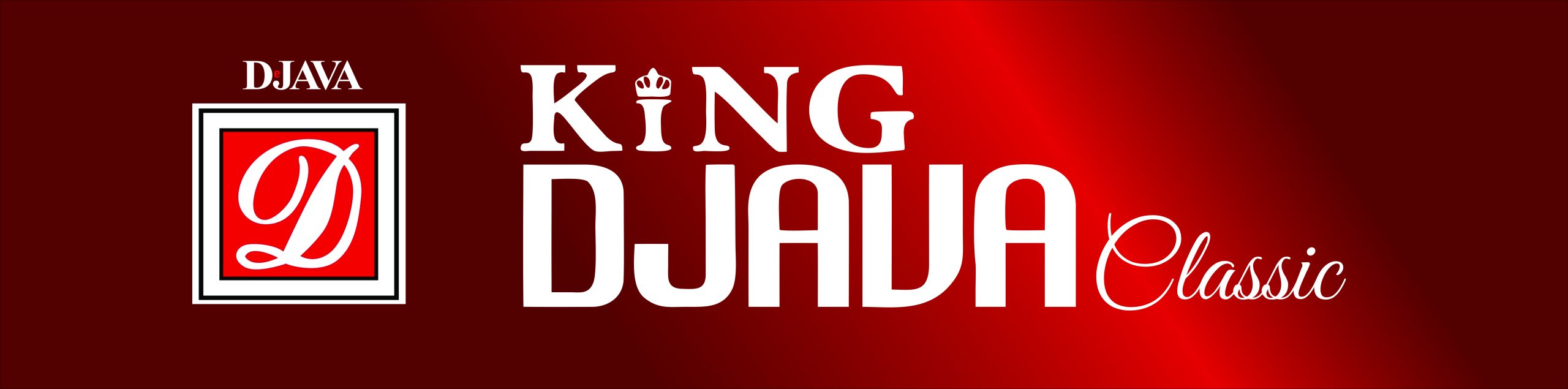Oleh: Hasibuddin
Opini – Di era digital saat ini, kritik pedas dari netizen terhadap institusi keagamaan — khususnya pesantren — seringkali muncul tanpa pemahaman yang memadai. Beberapa warganet dengan sigap melabel pesantren sebagai institusi “perbudakan”, menilai bahwa santri dipaksa bertingkah, bekerja, dan taat secara buta terhadap kiai.
Padahal narasi semacam itu jauh dari esensi pendidikan pesantren yang sesungguhnya. Dalam tulisan ini, kita akan memaparkan data dan analisis untuk membantah tuduhan-tuduhan keliru tersebut, serta mengajak masyarakat bersikap lebih objektif ketika mengomentari pesantren.
Mari kita lihat data faktual mengenai penyebaran pesantren dan jumlah santri di Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Agama per 4 Oktober 2025, ada 42.391 pondok pesantren di seluruh Indonesia.
Dari jumlah ini, sebagian besar adalah pesantren tradisional yang mengajar kitab kuning, dan sebagian lagi menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan formal.
Jumlah santri yang terlibat dalam sistem pesantren juga sangat masif. Misalnya menurut data Kementerian Agama tahun 2024, terdapat 4.847.197 orang santri di sekitar 41.599 pesantren. Artinya pesantren tidak bisa dianggap sebagai fenomena lokal atau marginal. Ia dalah bagian besar dari infrastruktur pendidikan keagamaan di Indonesia.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberi pesantren pengakuan hukum sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini mengatur standar bagaimana pesantren berdiri, fungsi pendidikan, dakwah, juga pemberdayaan. Pesantren yang memenuhi syarat formal wajib diketahui keberadaannya ke pemerintah desa atau kelurahan, dan terdaftar melalui mekanisme pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pesantren bukanlah institusi tanpa pengaturan atau pengawasan.
Menepis Tudingan Miring Netizen
Salah satu tuduhan paling keras yang sering muncul adalah bahwa santri diperlakukan seperti budak, dibebani tugas tanpa pilihan. Namun, realitasnya berbeda. Banyak santri yang secara sukarela memilih pesantren, tinggal di pondok/asrama, menjalankan tugas kebersihan, membantu kegiatan bersama, dan mengabdi kepada kiai serta gurunya bukan karena paksaan. Ini adalah bagian dari pendidikan adab, disiplin dan pembelajaran kehidupan. Tidak ada unsur kesewenang-wenangan seperti dalam konsep perbudakan.
Kedua, banyak netizen mengira bahwa karena santri membayar SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), maka dia seharusnya menjadi klien atau konsumen, dan bukan santri yang tunduk terhadap aturan pesantren. Padahal, SPP di pesantren mencakup biaya makan, listrik, air, pemeliharaan asrama, fasilitas belajar, dan administrasi lainnya. SPP bukan gaji untuk guru agar mereka “dikorbankan” dalam bentuk kerja atau khidmah yang dianggap berlebihan.
Di pesantren elit, SPP bulanan bisa mencapai Rp 1,6 juta hingga Rp 2 juta tergantung fasilitas dan program. Namun sebagian besar pesantren di Indonesia tidak meminta biaya seperti itu. Banyak pesantren yang SPP-nya jauh di bawah angka jutaan rupiah, bahkan sekitar Rp 500 ribu per bulan atau kurang. Ini menunjukkan bahwa komentar generalisasi bahwa pesantren mahal sangat keliru dan menyakitkan bagi khalayak yang kurang mampu.
Semula saya memaklumi karena netizen memang beragam. Ada yang waras dan ada pula yang setengah waras. Tapi rupanya, media massa dan influencer turut memicu persepsi negatif dengan framing yang instan dan sensasional.
Mereka kadang menggambarkan asrama atau khidmah sebagai bentuk “eksploitasi”. Padahal dalam banyak kasus, kehidupan asrama adalah bagian dari sistem pendidikan pesantren yang dirancang untuk membentuk karakter, tanggung jawab, disiplin, kepedulian terhadap sesama, dan kemandirian.
Perlu dicermati bahwa sebagian besar komentar negatif datang dari mereka yang belum pernah mengalami dunia pesantren. Karena minim pengalaman langsung, mereka mudah mengeneralisasi bahwa semua pesantren itu elit—yang fasilitasnya mewah—dan bahwa santri hidup dibawah tekanan ekstrim. Padahal realitas di lapangan sangat beragam. Ada pesantren sederhana, ada yang modern, ada yang biaya rendah, dan ada yang memiliki fasilitas yang lebih komplet, bahkan ada pesantren yang menggratiskan biaya makan untuk santrinya.
Keinginan Viral vs Konsistensi Pemahaman
Ada juga motif yang lebih buruk dari ocehan miring netizen atau framing biadap beberapa media massa hingga para influencer. Keinginan viral. Dalam budaya media sosial, komentar kontroversial seringkali lebih cepat menjaring perhatian. Sayangnya, agar cepat viral, banyak yang rela keluar dari batas sopan dan objektif. Saat dikoreksi, mereka sering kali membela diri dengan dalih “hak bebas berpendapat.” Padahal kebebasan berpendapat tetap terikat etika, akurasi, dan tanggung jawab.
UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan landasan hukum yang mengakui dan mengatur pesantren sebagai lembaga pendidikan. UU ini tidak mendefinisikan bahwa santri adalah pekerja atau budak, melainkan menyebutkan secara jelas bahwa pesantren berkedudukan sebagai lembaga pendidikan formal atau nonformal, dan bahwa santri yang bermukim di pondok memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan pesantren.
UU juga menegaskan bahwa pendirian pesantren dilakukan oleh masyarakat, yayasan, organisasi keagamaan, atau perseorangan yang memenuhi kriteria tertentu—termasuk pondok/asrama, masjid/musala, kajian kitab kuning atau kegiatan pendidikan Islam lainnya. Regulasi ini memperjelas bahwa ada standar yang harus dipenuhi, dan santri tidak semata-mata “dipaksa” tanpa aturan.
Lalu mengapa harus bijak dan berpikir kompleks untuk mengetahui realitas pesantren?
Pertama, pesantren memiliki sejarah panjang dalam peranannya mencetak ulama, menjaga tradisi Islam, membangun moral dan akhlak. Tuduhan yang tidak berdasar seperti “perbudakan” merusak martabat dan kepercayaan terhadap lembaga yang telah menjadi pilar pendidikan keagamaan Indonesia.
Kedua, melindungi santri dari stigma. Santri yang memilih untuk hidup di pesantren akan mendapat beban psikologis jika lingkungan luar terus menyebut mereka sebagai “korban sistem”. Ini bisa mengurangi semangat mereka, membuat mereka malu atau minder terhadap pilihan hidup yang sesungguhnya bernilai tinggi.
Ketiga, Mendorong dialog konstruktif.
Jika ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki di pesantren — misalnya transparansi biaya, kondisi fasilitas, atau pemenuhan standar keamanan bangunan — kritik harusnya konstruktif. Bukan hinaan generalis. Media dan masyarakat harus mau mendengarkan data, mengambil contoh nyata, dan menawarkan solusi.
Terakhir, Menegakkan etika kritik di ruang publik. Sebagai warga digital, kita memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menyebarkan info sesat. Sebaiknya jika tidak pernah mengerti betul tentang bagaimana pesantren dijalankan, jangan gegabah menyimpulkan. Prinsip tabayun (klarifikasi) penting: periksa fakta sebelum menuding.
Komentar negatif dari netizen seperti menyebut pesantren sebagai bentuk perbudakan, adalah refleksi dari minimnya pemahaman akan keterkaitan antara pendidikan, adab, budaya, dan agama.
Data resmi menunjukkan bahwa pesantren di Indonesia jumlahnya puluhan ribu, dengan jutaan santri yang memilih dunia pesantren secara sukarela. Ribuan pesantren beroperasi dengan berbagai tingkat biaya, dari yang biasa hingga elite.
Komentar sinis yang mengeneralisasi hanya merugikan, merendahkan pesantren dan menyakiti santri yang ikhlas mengabdi, memilih hidup dengan penuh disiplin, dan menjalankan tradisi yang telah lama teruji.
Kritik boleh saja, bahkan diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial. Namun kritik sejati adalah yang berdasarkan fakta, adab, dan keinginan memperbaiki, bukan sekadar mencerca agar terdengar “keren di kolom komentar”.
Semoga ocehan semacam itu perlahan tertahan oleh data, oleh pemahaman, dan oleh rasa hormat terhadap institusi yang telah berjasa bagi pendidikan bangsa. Pesantren bukan tempat perbudakan; ia adalah ladang iman, adab, dan perjuangan yang layak dihormati dan dilindungi.
*Penulis adalah manusia yang pernah ngalap barokah kepada Kiai Basyiruddin Amien, Pengasuh Pondok Pesantren Al Amien, Saangan, Kowel Pamekasan.